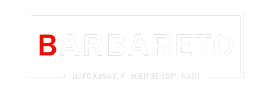Selong – Ada satu peristiwa kecil yang tak pernah saya lupa. Beberapa tahun lalu, di sebuah dusun di kaki Rinjani, seorang perempuan tua melantunkan syair dalam bahasa Sasak yang nyaris tak saya pahami sepenuhnya. Tapi sorot matanya, dan mereka yang mendengarkan, seolah berbicara dengan fasih. Di sela dentang gong, saya melihat sesuatu yang lebih dari sekadar pertunjukan. Itu adalah ritual perlawanan: melawan lupa, melawan lenyap.
Lombok Timur, tempat saya lahir dan bertumbuh adalah ladang subur kebudayaan. Ia menyimpan jejak panjang peradaban agraris, ritus adat, seni tutur, tenun, dan pengetahuan lokal yang hidup berdampingan dalam harmoni yang sunyi.
Justru dalam kesunyian itu, kebudayaan kita terancam. Bukan karena ditinggalkan masyarakat semata, melainkan karena kerap luput dari perhatian pemerintah.
Di sinilah seharusnya Rencana Strategis (Renstra) Kebudayaan Daerah hadir bukan sebagai dokumen mati, melainkan sebagai naskah kehidupan. Sebuah upaya menjahit ulang ingatan kolektif kita.
Sesekali saya pernah ikut dalam diskusi kebijakan, saya tahu bahwa Renstra adalah bagian dari siklus perencanaan lima tahunan yang disusun oleh OPD, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Renstra memuat visi, misi, strategi, program, kegiatan, bahkan indikator kinerja yang seolah rapi di atas kertas. Namun saya sering bertanya siapa yang menulisnya? Dan untuk siapa?
Jika penyusunannya tak melibatkan pelaku budaya, bagaimana mungkin ia mewakili denyut nadi masyarakat? Jika indikatornya sekadar jumlah even atau pelatihan, bagaimana bisa ia menjaga keberlanjutan nilai?
Saya percaya Renstra bukan hanya perihal anggaran dan program. Ia adalah perahu ingatan yang mengangkut nilai, identitas, dan keberlanjutan lintas generasi.
Harapan ke Dewan Kebudayaan
Dalam rancangan ideal, Dewan Kebudayaan Daerah (DKD) sebelumnya bernama Dewan Kesenian Daerah seharusnya menjadi ruang artikulasi dan advokasi nilai-nilai budaya lokal. Sebuah jembatan antara dunia komunitas dan dunia birokrasi.
Tapi di Lombok Timur, keberadaan DKD seringkali hanya simbolik di-SK-kan, tapi tak dihidupkan. Mereka jarang dilibatkan dalam penyusunan kebijakan, apalagi diberi ruang dan anggaran.
Padahal, saya pernah duduk bersama sejumlah seniman dan budayawan desa yang punya gagasan luar biasa tentang festival rakyat yang berbasis ritus panen, tentang digitalisasi tembang tradisional, bahkan tentang peta kuliner etnik sebagai aset ekonomi. Tapi semua itu menguap karena mereka tak tahu harus bicara kepada siapa. Dewan tak hadir. Negara tak mendengar.
Renstra yang partisipatif tak akan pernah terwujud bila struktur seperti DKD tak diberi peran nyata. Mereka seharusnya tidak hanya “dilibatkan”, tetapi menjadi penghela utama kebijakan.
Kebudayaan bukan milik dinas. Ia milik masyarakat. Maka, merancang masa depan budaya seharusnya bukan kerja teknokratik semata.
Saya membayangkan nanti penyusunan Renstra bisa dilakukan di bale-bale kampung, di amben rumah adat, di tengah komunitas petani, penenun, pemangku adat, pemuda desa, dan pelaku seni. Di sana, bukan hanya dokumen yang disusun, tapi juga komitmen sosial yang ditanam.
Dari pengalaman saya menghadiri diskusi perencanaan daerah, seringkali budaya hanya menjadi “pelengkap narasi” dalam RPJMD. Nilai dan pengetahuan lokal tak diberi ruang sebagai sumber solusi pembangunan.
Padahal, dalam banyak kasus, solusi terhadap ketahanan pangan, mitigasi bencana, atau pemberdayaan perempuan, sudah hidup dalam kearifan lokal.
Pemerintah daerah harus lebih berani melihat budaya sebagai modal strategis. Bukan sekadar identitas, tapi sumber daya pembangunan. Dan Renstra Kebudayaan adalah alat transformasi itu.
Pelestarian seringkali dilakukan dalam sunyi. Seorang pemuda di Pringgabaya mencatat permainan rakyat agar tidak hilang. Seorang pengajar di Sakra merekam syair lama dalam bentuk audio. Di Suela, perempuan petani menyimpan ramuan pertanian organik warisan leluhur.
Namun mereka berjalan sendiri. Tanpa dukungan, tanpa jaringan, tanpa apresiasi. Program dalam Renstra seperti “inventarisasi budaya” atau “pelatihan seni” harus menjangkau mereka. Bahkan melibatkan mereka sebagai narasumber utama, bukan sebagai objek binaan.
Saya membayangkan indikator keberhasilan pelestarian tidak hanya berupa “jumlah festival” atau “jumlah dokumen budaya”, tapi juga jumlah pelaku budaya yang bertahan dan beregenerasi.
Menulis Komitmen Kultural
Renstra juga seharusnya menghubungkan kebudayaan dengan kesejahteraan. Bagaimana program promosi budaya mendukung ekonomi lokal? Bagaimana desa wisata berbasis budaya bisa mencegah urbanisasi? Bagaimana nilai lokal dimasukkan dalam pendidikan dasar, agar anak-anak tak asing dengan akar mereka sendiri?
Saya percaya, kebudayaan hanya bisa lestari jika ia hidup dalam keseharian. Bukan dikurung di museum atau ditampilkan saat festival saja.
Maka saya berharap, penyusunan Renstra di masa depan tak hanya menyentuh program besar seperti pemugaran cagar budaya, tapi juga hal-hal sederhana seperti penguatan komunitas tenun, penerbitan buku cerita rakyat, digitalisasi arsip desa, atau pelatihan konten budaya berbasis media sosial.
Khasanah budaya kita kaya, tapi rapuh. Kaya karena ia tumbuh dari keragaman sejarah, alam, dan pengalaman hidup masyarakat kita. Rapuh karena tidak semua warisan itu dicatat, dihidupi, dan dilanjutkan. Tanpa perencanaan yang berpihak dan melibatkan, budaya bisa menjadi pusaka yang terlupakan.
Renstra Kebudayaan bukanlah solusi akhir, tetapi ia bisa menjadi awal, jika ditulis dengan kesadaran, dijalankan dengan keberanian, dan dijaga bersama.
Kita membutuhkan ruang-ruang partisipatif yang otentik, keberanian untuk menyusun indikator baru yang lebih manusiawi, serta komitmen pemerintah untuk mendanai kebudayaan bukan sebagai proyek, tapi sebagai kebutuhan hidup. Karena pada akhirnya, yang kita jaga bukan hanya tarian, bahasa, atau ritus. Tapi jati diri, memori, dan harapan.
Itu semua, hanya bisa ditulis jika kita mulai mendengarkan kembali suara dari desa-desa, dari dusun-dusun, dari tempat di mana budaya tidak mati, tapi sedang menunggu untuk diperhatikan!.
Harianto. Jurnalis lepas & peneliti budaya di LRC
Berita lainnya klik disini