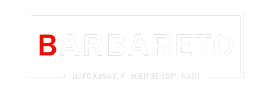Oleh: Amrillah – Ketua BDBD Lombok Tengah
Dalam ingatan kolektif masyarakat, pemerintah adalah entitas tunggal. Bagi warga yang terperosok di lubang jalan, petani yang terisolasi akibat jembatan putus, atau pejalan kaki yang terganggu aroma busuk tumpukan sampah di drainase kota, mereka tidak melihat warna marka jalan atau kode registrasi aset. Bagi mereka, hanya ada satu tuntutan logis: negara harus hadir.
Namun, di balik meja birokrasi, realitasnya tidak sesederhana itu. Ada sekat-sekat regulasi yang memisahkan mandat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Belakangan ini, tren mengadukan seluruh persoalan teknis di daerah langsung ke meja Gubernur—terutama melalui kanal media sosial—menjadi fenomena menarik.
Di satu sisi, ini menunjukkan tingginya harapan dan kepercayaan publik pada kepemimpinan di tingkat provinsi. Namun di sisi lain, fenomena ini menyingkap adanya “kabut kewenangan” yang perlu diperjelas agar tata kelola pemerintahan tidak tumpang tindih dan terjebak dalam pola kerja reaktif.
Sekat Regulasi Infrastruktur
Persoalan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan, adalah titik paling rawan terjadinya salah sasaran pengaduan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, kewenangan penyelenggaraan jalan dibagi secara tegas. Secara visual, kita mengenal marka kuning untuk jalan nasional dan provinsi, serta marka putih untuk jalan kabupaten/kota.
Ketika sebuah jembatan putus di pelosok desa atau jalan lingkungan rusak parah, secara hukum mandat perbaikannya berada di tangan Pemerintah Kabupaten. Namun, sering kali keterbatasan fiskal di tingkat daerah membuat penanganan menjadi lamban. Akibatnya, bola panas dilemparkan ke Pemerintah Provinsi.
Masyarakat perlu memahami bahwa Gubernur memiliki keterbatasan legal-formal untuk mengintervensi anggaran pada aset yang bukan milik provinsi. Memaksa pemerintah provinsi mengambil alih seluruh kerusakan infrastruktur bukan hanya menabrak aturan tertib anggaran, tetapi juga berpotensi menciptakan maladminstrasi. Jembatan bukan sekadar pelengkap jalan; ia adalah urat nadi ekonomi yang pemeliharaannya harus dilakukan oleh instansi yang memiliki otoritas sesuai tingkatannya agar akuntabilitasnya terjaga.
Otonomi dan Sampah
Kasus tumpukan sampah di saluran drainase perkotaan yang kerap viral menjadi studi kasus yang menarik. Secara eksplisit, UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah memberikan mandat penuh kepada pemerintah kabupaten/kota sebagai eksekutor utama. Mulai dari pembersihan selokan, pengangkutan, hingga pengelolaan akhir adalah ranah otonomi kota.
Ketika Gubernur harus turun tangan atau memberikan instruksi langsung untuk urusan selokan, ini sebenarnya adalah sebuah “alarm” bagi birokrasi di tingkat bawah. Langkah tersebut memang menunjukkan kepemimpinan akseleratif—sebuah diskresi untuk memutus kebuntuan (deadlock). Namun, secara sistemik, tata kelola tidak bisa terus-menerus mengandalkan intervensi “pemadam kebakaran” dari tingkat atas.
Jika setiap sumbatan selokan harus menunggu instruksi Gubernur, maka fungsi Pemerintah Kota sebagai garda terdepan pelayanan publik patut dipertanyakan. Kedisiplinan instansi teknis di tingkat kota seharusnya berjalan secara autopilot tanpa perlu menunggu sebuah isu menjadi viral terlebih dahulu.
Integrasi Digital
Untuk mengurai benang kusut kewenangan ini, literasi publik saja tidak cukup. Diperlukan sebuah Sistem Pengaduan Terintegrasi yang mampu menjembatani aduan warga ke meja yang tepat secara otomatis.
Kita tidak bisa melarang warga mengadu ke Gubernur melalui media sosial, karena itu adalah kanal demokrasi paling cair saat ini. Namun, pemerintah perlu membangun backend digital di mana setiap aduan yang masuk ke provinsi-jika itu merupakan ranah kabupaten/kota-langsung terdistribusi secara sistem ke dinas terkait di tingkat bawah dengan notifikasi yang wajib ditindaklanjuti.
Dengan sistem pengaduan yang terintegrasi dan transparan, masyarakat tidak perlu lagi dipusingkan oleh status jalan atau jenis kewenangan. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara digital: memantau seberapa cepat Pemerintah Kabupaten/Kota merespons keluhan warga.
Pada akhirnya, pelayanan publik memang urusan nurani yang melampaui batas administrasi. Namun, sistem birokrasi yang sehat adalah sistem yang setiap levelnya berfungsi optimal. Jangan sampai energi pemimpin di tingkat provinsi habis terkuras untuk mengurusi persoalan mikro yang seharusnya tuntas di meja camat atau wali kota. Konektivitas dan kebersihan wilayah adalah kerja kolaborasi, di mana rakyat paham haknya, dan setiap tingkatan pemerintah sadar akan kewajibannya.